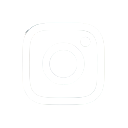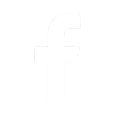Becermin dari Krisis Nilai Tukar Turki

Perekonomian Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Dari sisi eksternal, berbagai risiko terus bermunculan. Belum selesai kita disugukan dengan perang dagang antara AS dengan sejumlah negara, khususnya China. Maka kita juga dikejutkan dengan terpuruknya nilai tukar Lira, Turki.
Sebagaimana diketahui, pada pertegahan Agustus 2018 lalu, nilai tukar Lira terjerembab sebesar 16% terhadap nilai tukar dollar AS. Ini merupakan pelemahan harian yang paling dalam. Membuat kinerja nilai tukar Lira menjadi yang terburuk di antara nilai tukar lainnya, khususnya di kawasan emerging.
Situasi ini pun membuat ekonomi Turki berada di ambang krisis. Jika tidak ditangani dengan serius dan komprehensif, bisa membuka ruang bagi terjadinya krisis ekonomi baru. Harus diakui dengan keterbukaan ekonomi global, permasalahan ekonomi di satu negara bisa memicu penjalaran (contagion) terhadap ekonomi negara-negara lain.
Harus diakui bahwa kejatuhan nilai tukar Lira ini merupakan buah dari tiadanya kehati-hatian, khususnya dalam pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN). Turki terlalu bergantung dengan ULN, khususnya yang berasal dari negara-negara di Eropa. Turki memanfaatkan rendahnya tingkat suku bunga pinjaman di Eropa untuk terus mengakumulasi ULN. Tidaklah mengherankan, pada tahun 2017, total ULN Turki (pemerintah dan Korporasi) menembus $ 453,2 miliar. Nilai ULN meningkat dua kali lipat dibandingkan posisi ULN tahun 2009.
ULN ini digunakan sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Tidaklah mengherankan, pada kuartal I-2018, ekonomi Turki bisa tumbuh sebesar 7,4% (yoy). Bahkan, pada kuartal III-2017 sempat menyentuh level 11,3% (yoy). Tidak banyak negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi ini, khususnya di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Namun, masalah mulai terjadi, yaitu ketika Bank Sentral di negara-negara maju, khususnya AS mulai menaikkan suku bunga kebijakannya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi.
Dana global balik kandang dan aliran dana keluar pun mulai berlangsung. Turki tidak bisa mengantisipasinya, karena terlalu terlena dengan ULN yang murah. Turki pun tidak disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal dan moneternya. Hal ini tecermin dari besarnya Defisit Transaksi Berjalan (DTB). Setidaknya, dalam sepuluh tahun terakhir, Turki terus didera oleh DTB yang besar. Tidak ada perbaikan yang signifikan.
Situasi makin tak kondusif, karena pemilik dana di pasar keuangan Turki memberikan hukuman dengan menarik dana mereka secara beramai-ramai. Pemilik dana telah mengingatkan bahwa Bank Sentral Turki (TCMB) tidak memiliki independensi. TCMB terlalu dikendalikan oleh pemerintah. Indikasi ini dapat terlihat dari kebijakan TCBM yang tetap mempertahankan suku bunga, meski tekanan inflasi sudah terjadi.
TCMB tetap mempertahankan suku bunga rendah, seiring adanya intervensi dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tetap menghendaki suku bunga rendah agar tidak menghambat masyarakat untuk mengakses kredit yang murah. Sehingga, bisa membuat perekonomian tetap tumbuh tinggi. Masalahnya, mempertahankan suku bunga yang rendah juga bisa mendorong morald hazard peminjam dengan menggunakan kredit yang diterima bukan untuk tujuan produktif. Tetapi untuk tujuan konsumtif yang tidak memberikan efek berganda pada perekonomian. Dengan berbagai permasalah internal ekonomi Turki ini dan adanya sanksi ekonomi dari AS membuat kejatuhan Lira tidak dapat dihindarkan.
Pengalaman Indonesia
Situasi yang terjadi di Turki mengingatkan kita pada apa yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997/98. Periode itu sering juga disebut dengan krisis moneter. Akar dari krisis ini dipicu oleh kejatuhan nilai tukar Bath, Thailand dan memicu efek penjalaran (contagion effect) pada Indonesia.
Saat itu, kinerja perekonomian Indonesia juga cukup menjanjikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7% yang membuat sejumlah lembaga keuangan dunia memberikan pujian. Indonesia pun dijuluki sebagai ‘Macan Asia’.
Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak dibangun di atas fondasi yang kuat. Tingginya ketergantungan terhadap ULN, lemahnya tata kelola di sektor perbankan, tidak independennya bank sentral, dan buruknya tata kelola pemerintah yang tecermin dari merebaknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah internal ekonomi Indonesia. Sehingga, ketika tekanan eksternal muncul, maka ambruklah fondasi yang lemah itu. Ekonomi Indonesia diterpa krisis.
Pengalaman krisis itu menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan. Dan, harus diakui telah banyak perbaikan yang terjadi sejak krisis moneter itu. Salah satunya, makin membaiknya kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan, khususnya perbankan. Sektor ini harus dijaga dengan regulasi yang ketat, karena inilah sektor yang menjadi jantung, sehingga aktivitas perekonomian bisa berdenyut.
Itulah sebabnya, ketika berbagai tekanan dan sentimen eksternal bermunculan, seperti krisis subprime mortgage (2008), krisis utang Eropa (2010), gejolak harga komoditas (2011), Taper Tantrum (2013), devaluasi nilai tukar yuan (2015), perekonomian Indonesia relatif bisa bertahan dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi sektor riil, seperti yang terjadi pada tahun 1997/98.
Meski begitu masih banyak pekerjaan rumah untuk memperkokoh fondasi ekonomi. Kita harus memberikan apresiasi pada pemerintah dalam empat tahun terakhir, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi, mengejar ketertinggalan infrastruktur, dan memperbaiki iklim investasi.
Meski begitu, masih banyak yang harus dibenahi. Lihat saja, ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Defisit Transaksi Berjalan (DTB) langsung memburuk. Pada kuartal II-2018, DTB kembali menembus level 3% terhadap PDB. Padahal, pada tahun 2017, masih di bawah level 2% terhadap PDB.
Memburuknya DTB ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih rapuh. Belum ada kemajuan di berbagai sektor, khususnya sektor manufaktur untuk mengungkit daya saing ekonomi. Bukan itu saja, sektor keuangan yang belum dalam membuat Indonesia masih tergantung pada pembiayaan eksternal, khususnya dari pembiayaan portofolio. Padahal, pembiayaan ini yang sangat rentan terimbas oleh sentimen dan ketidakpastian.
Dengan fondasi ekonomi yang belum solid inilah yang membuat rupiah menjadi rentan bergejolak dan melemah. Dan harus diakui bahwa sejak tahun 2000, nilai tukar rupiah memang cenderung melemah. Dan, untuk mengatasi pelemahan itu, maka kebijakan jangka pendek selalu menjadi solusi, seperti menaikkan suku bunga dan melakukan kebijakan pembatasan impor. Yang imbasnya bisa memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi.
Semoga kejatuhan nilai tukar Lira, Turki menjadi sebuah reminder bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus memperkokoh fondasi ekonomi. Jika tidak, maka perekonomian Indonesia akan selalu rentan diterjang oleh ketidakpastian eksternal dan berimbas pada terganggunya stabilitas makroekonomi dan tertekannya kinerja pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat lah yang menjadi taruhannya.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya