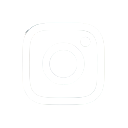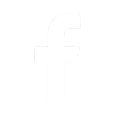Ekonomi Indonesia dan Perang Dagang

Kebijakan proteksionisme Donald Trump yang pernah dijanjikannya telah direalisasikan. Pada Juni 2018, Trump menetapkan tarif tambahan sebesar 10% untuk Aluminium dan 25% untuk Baja. Trump berkilah bahwa harga Aluminium dan Baja impor yang sangat murah telah memukul industri lokal dan memicu gelombang pengangguran. Sontak, kebijakan ini memicu kegeraman sejumlah negara, seperti China, Meksiko, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa.
Selain itu, Trump juga berencana akan mengenakan tambahan tarif senilai $ 350 miliar terhadap produk otomotif dan suku cadang. Kondisi ini membuat Uni Eropa berang dan akan melakukan aksi pembalasan yang sama terhadap produk AS. Hal inilah yang membuat Harley Davidson (HD) sebagai produsen “motor gede” dan ikon kekuatan manufaktur AS ikut kena getahnya. Harga HD menjadi tidak kompetitif.
HD pun mengancam akan memindahkan basis produksinya ke luar negeri, jika kebijakan ini tidak direvisi. Namun, dikecam Trump dengan menaikkan tarif pajak yang tinggi pada HD, jika berani memindahka basis produksinya. Tidak berhenti sampai di situ. Trump kembali berulah. Pada 6 Juli 2018, ia kembali mengenakan tarif tambahan sebesar 25% terhadap produk-produk China senilai $ 34 miliar. Hal ini membuat pemerintah China berang dan menyatakan akan melakukan pembalasan (retaliation) terhadap produk-produk AS dengan nilai yang sama.
Aksi pembalasan China ini membuat Trump berang. Ia pun berencana akan memperluas pengenaan tarif terhadap produk-produk China lainnya hingga nilainya mencapai $ 400 miliar. Pemerintah China tidak takut dan akan terus melawan. Kebijakan Trump menekan China tidak dapat dilepaskan dari defisit perdagangan dengan China yang terus melebar. Tahun 2017 nilai defisit dagang dengan China mencapai $ 375 miliar.
Dengan mengenakan tarif tinggi, maka diharapkan akan menekan banjir produk-produk China yang murah dan kembali dapat menggairahkan daya saing industri lokal yang pada akhirnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor manufaktur. Penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran menjadi salah satu janji kampaye Trump. Meski begitu, kebijakan Trump ini berpotensi memicu risiko baru yang bisa memengaruhi arah pemulihan perekonomian global yang saat ini sedang berlangsung.
Salah satu risiko yang patut diwaspai ialah perang mata uang (currency war). Pemerintah China berpotensi untuk mengambil kebijakan devaluasi nilai tukar Yuan untuk mengompensasi tambahan tarif ini dan mendorong daya saing produk ekspornya. Jika ini terjadi, maka negara lain, seperti Jepang bisa mengikuti, karena tidak ingin juga kehilangan daya saing ekspornya. Alhasil, perang dagang memicu perang mata uang (currency war), di mana kondisi seperti tidak diharapkan oleh siapa pun.
Indikasi China melakukan devaluasi Yuan cukup nyata. Sepanjang Juni 2018, nilai tukar Yuan telah terdepresiasi sebesar 3,2% ke level 6,28 per dollar AS. Ini merupakan pelemahan bulanan terbesar sepanjang tahun ini. Bahkan, sejumlah analis meramal bahwa tren pelemahan Yuan ini masih berpotensi berlanjut, jika tensi perang dagang meningkat. Sebagai informasi, nilai tukar Yuan sampai pertengahan Juli 2018 masih terus melemah hingga ke level 6,69 per dollar AS.
Pelemahan Yuan ini berpotensi menekan kinerja sektor keuangan global. Berkaca pada tahun 2015, ketika Bank Sentral China (PoBC) melakukan devaluasi Yuan telah membuat pasar keuangan global kala itu terguncang hebat. Hampir semua pasar saham berguguran, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara melonjak, dan nilai tukar global, khususnya di emerging market terdepresiasi. Indonesia tidak luput dari guncangan tersebut.
Apakah kondisi tahun 2015 tersebut bisa terulang? Sangat ditentukan oleh tindakan Trump sendiri. Itulah sebabnya, ekslasi perang dagang ini telah membuat pasar keuangan global bergerak bagai bandul. Investor terlihat sangat hati-hati menyikapi arah dari perang dagang dua raksasa ekonomi dunia ini.
Itulah sebabnya dalam World Economic Outlook (WEO) 2018 terbarunya yang dirilis oleh Dana Moneter International (IMF) pada (16/7) menyimpulkan bahwa perang dagang ini telah memicu meningkatnya risiko global, khususnya dalam jangka pendek, meski perekonomian global tetap solid.
Peluang Indonesia
Perang dagang ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, meski dua negara ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Sebagai catatan, sepanjang Januari-Juni 2018, Indonesia mengalami surplus dagang dengan AS sebesar $ 4,12 miliar dan defisit dengan China sebesar $ 8,28 miliar.
Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan dapat mengambil peluang di dari pusaran perang dagang ini. Pertama, ceruk pasar eskpor China yang hilang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dengan AS.
Itulah sebabnya, Indonesia harus dapat menyakinkan pemerintah AS dengan lobi dan diplomasi yang baik. Diharapkan pemerintah AS juga melunak terkait rencananya untuk mencabut pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).
Kedua momentum untuk memperkuat sektor manufaktur dan meningkatkan industri bahan baku dan penolong yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor dan sekaligus dapat mengerem laju produk impor.
Indonesia harus berani untuk keluar dari ketergantungan terhadap produk-produk komoditas mentah (raw material) yang sifatnya tidak berkelanjutan, apalagi ketika kinerja perekonomian global, khususnya China mengalami tekanan.
Ketiga, pemerintah harus lebih intensif dan gencar untuk membuka pasar ekspor baru yang potensinya sangat besar, tetapi masih kurang dilirik, seperti Amerika Latin, Eropa Timur, Afrika, dan Arab.
Keempat, sektor pariwisata juga harus terus digenjot sebagai sektor komplementer dari sektor ekspor. Pemerintah bahkan telah menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sayangya, Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia dan Thailand dalam mendulang devisa di sektor ini. Banyak masalah yang harus diperbaiki, seperti buruknya infrastruktur, perizinan yang berbelit, dan rendahnya skill Sumber Daya Manusia (SDM).
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya