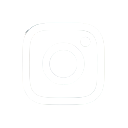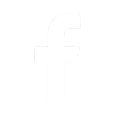Keniscayaan Utang

Total outstanding utang pemerintah sampai dengan Mei 2017 mencapai Rp 3.672,33 triliun. Utang ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.943,7 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp 728,6 triliun (19,8%).
Padahal, pada tahun 2014, total utang pemerintah ‘masih’ sebesar Rp 2.608,78. Artinya, sepanjang periode 2015-Mei 2017, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menambah utang baru sebesar Rp 1.063,55 triliun.
Jumlah utang ini masih bisa bertambah hingga akhir tahun ini akibat pelebaran defisit di APBN-P 2017 dari 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,9% terhadap PDB. Tambahan utang baru akibat pelebaran defisit ini diperkirakan sebesar Rp 76,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY-Boediono (2010-2014), penambahan utang baru ‘hanya’ sekitar Rp 1.019 triliun. Artinya, pemerintahan Jokowi-Kalla sangat agresif dalam menyedot utang baru.
Kondisi inilah yang membuat utang pemerintah kembali menjadi sorotan dan pemberitaan media dalam beberapa waktu terakhir. Pro dan kontra pun bermunculan.
Perlu dicatat bahwa ada beberapa alasan yang membuat pemerintah harus menambah utang, seperti akumulasi utang pemerintah di masa lalu (debt legacy), dampak krisis ekonomi 1997/98 yang membuat pemerintah harus membayar bunga obligasi rekap, depresiasi nilai tukar, dan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran.
Kubu yang pro (pihak pemerintah) menyatakan bahwa penambahan utang baru tidak masalah, selama ditujukan untuk membiayai sektor-sektor yang dapat menimbulkan multiflier effect dan nilai tambah pada perekonomian, seperti infrastruktur.
Kubu ini juga berpendapat bahwa di tengah kelesuan ekonomi yang membuat penerimaan sukar digenjot, sementara belanja harus didorong, membuat penambahan utang baru menjadi tidak terhindarkan agar perekonomian makin tidak terkapar.
Apalagi, kapasitas pemerintah untuk menambah utang baru masih sangat besar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rasio utang terhadap PDB di level 28%. Rasio ini terendah di antara negara sekawasan, seperti Jepang (250,40%), Malaysia (53,2%), China (46,20%), Filipina (42,10%), Thailand (41,20%), dan India (69,50%).
Sementara, bagi kubu yang kontra berpendapat bahwa penambahan utang baru akan yang terus terjadi akan memasung kemampuan APBN untuk bermanuver, khususnya ketika terjadi krisis, memicu ketergantungan, dan membebani generasi yang akan datang.
Bukan itu saja, tingkat bunga (yield) utang relative mahal, karena diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.
Saat ini, tingkat yield SBN tenor 10 tahun di level 6,9%. Tertinggi dibandingkan dengan Malaysia (3,96%), Filipina (5,1%), Thailand (2,46%), Vietnam (5,47%), Singapura (2,1%), Korea Selatan (2,24%), China (3,55%), India (6,5%).
Yield yang tinggi inilah yang membuat pemodal asing terus memburu SBN. Hingga Juni 2017, total outstanding pemodal asing di SBN mencapai Rp 770,55 triliun atau sekitar 39% dari total SBN yang beredar di pasar.
Alhasil, ketika pemerintah membayar bunga SBN, maka pemodal asing inilah yang paling menikmatinya. Tahun ini, alokasi dana untuk membayar bunga utang mencapai Rp 221,2 triliun (16,8% dari total belanja pemerintah pusat).
Ironisnya, pemodal asing ini sewaktu-waktu bisa membawa keluar (capital outflow) keutungan investasi dari SBN itu, ketika terjadi perubahan sentimen. Dalam situasi inilah, rupiah akan cenderung tertekan dan menggerus cadangan devisa.
Selain itu, kubu yang kontra juga berpendapat bahwa rasio utang terhadap PDB tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk mengukur utang masih aman. Sebab, jika diukur berdasarkan rasio penerimaan ekspor terhadap PDB (debt to service ratio/DSR) dan keseimbangan defisit primer, maka posisi utang pemerinta saat ini harus jadi perhatian serius.
Sampai kuartal I-2017, posisi DSR di level 52%. Artinya, setengah dari hasil ekspor digunakan untuk membayar utang. DSR ini naik tajam dibandingkan tahun 2012 yang di level 35%. Sedangkan, defisit keseimbangan primer tahun 2016 telah menembus Rp 125,8 triliun. Naik tajam dari tahun 2102 sebesar Rp 52,8 triliun.
Per definisi, defisit keseimbangan primer merupakan hasil dari pengurangan penerimaan dengan belanja di luar pembayaran pokok dan bunga utang. Makin melebarnya defisit keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan untuk membayar utang jatuh tempo berasal dari utang baru yang diterbitkan alias gali lubang tutup lubang.
Keniscayaan
Meskipun pemerintahan Jokowi-Kalla menyedot utang dalam jumlah besar dalam 2,5 tahun terakhir, tetapi tetapi ada beberapa kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan rezim sebelumnya.
Pertama, utang tidak lagi dipakai untuk membiayai subsidi yang tidak produktif, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik. Dalam tiga tahun terakhir, subsidi BBM dan Listrik mengalami pemangkasan yang siginifikan dari Rp 341,8 triliun (2014) menjadi Rp 77,3 triliun (2017). Sementara, belanja infrastruktur naik tajam dari Rp 264 triliun (2014) menjadi Rp 387,3 triliun (2017).
Ke depan, pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN untuk membangun infrastruktur dengan menggali potensi sumber-sumber pembiayaan non APBN (PINA), baik melalui pasar modal, sekuritisasi aset, BUMN, dan kerja sama sektor swasta.
Kedua mendorong efisiensi belanja dengan memangkas belanja yang tidak memberi efek pengganda pada perekonomian, seperti belanja barang. Tahun ini nilainya sebesar Rp 16 triliun.
Ketiga mendorong kualitas budgeting yang diharapkan dapat memperbaiki penyerapan belanja. Ini merupakan kelemahan terbesar yang sampai saat ini belum bisa hilang dari tubuh birokrasi. Buruknya kualitas penyerapan belanja inilah yang membuat tambahan utang menjadi mubazir.
Keempat mendorong dan memaksimalkan penerimaan, khususnya perpajakan. Harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak selama ini masih jauh dari potensinya.
Hal ini dapat tecermin dari kecilnya rasio wajib pajak terhadap jumlah penduduk dan rendahnya kepatuhan membayar pajak. Kondisi inilah yang membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB dalam lima tahun terakhir mandek di level 10%-11%. Tertinggal jauh dari Malaysia (14%), Thailand (16%), Filipina (13%), Singapura (13%).
Untuk itulah, pemerintah telah menempuh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan menerbitkan Perpu nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan agar potensi pajak yang sangat besar itu dapat digali.
Pendek kata, jika tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan, khususnya pajak dan tidak ada perbaikan yang mendasar terhadap kualitas penganggaran belanja dan penyerapannya, maka penambahan utang merupakan sebuah keniscayaan.
Total outstanding utang pemerintah sampai dengan Mei 2017 mencapai Rp 3.672,33 triliun. Utang ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.943,7 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp 728,6 triliun (19,8%).
Padahal, pada tahun 2014, total utang pemerintah ‘masih’ sebesar Rp 2.608,78. Artinya, sepanjang periode 2015-Mei 2017, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menambah utang baru sebesar Rp 1.063,55 triliun.
Jumlah utang ini masih bisa bertambah hingga akhir tahun ini akibat pelebaran defisit di APBN-P 2017 dari 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,9% terhadap PDB. Tambahan utang baru akibat pelebaran defisit ini diperkirakan sebesar Rp 76,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY-Boediono (2010-2014), penambahan utang baru ‘hanya’ sekitar Rp 1.019 triliun. Artinya, pemerintahan Jokowi-Kalla sangat agresif dalam menyedot utang baru.
Kondisi inilah yang membuat utang pemerintah kembali menjadi sorotan dan pemberitaan media dalam beberapa waktu terakhir. Pro dan kontra pun bermunculan.
Perlu dicatat bahwa ada beberapa alasan yang membuat pemerintah harus menambah utang, seperti akumulasi utang pemerintah di masa lalu (debt legacy), dampak krisis ekonomi 1997/98 yang membuat pemerintah harus membayar bunga obligasi rekap, depresiasi nilai tukar, dan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran.
Kubu yang pro (pihak pemerintah) menyatakan bahwa penambahan utang baru tidak masalah, selama ditujukan untuk membiayai sektor-sektor yang dapat menimbulkan multiflier effect dan nilai tambah pada perekonomian, seperti infrastruktur.
Kubu ini juga berpendapat bahwa di tengah kelesuan ekonomi yang membuat penerimaan sukar digenjot, sementara belanja harus didorong, membuat penambahan utang baru menjadi tidak terhindarkan agar perekonomian makin tidak terkapar.
Apalagi, kapasitas pemerintah untuk menambah utang baru masih sangat besar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari rasio utang terhadap PDB di level 28%. Rasio ini terendah di antara negara sekawasan, seperti Jepang (250,40%), Malaysia (53,2%), China (46,20%), Filipina (42,10%), Thailand (41,20%), dan India (69,50%).
Sementara, bagi kubu yang kontra berpendapat bahwa penambahan utang baru akan yang terus terjadi akan memasung kemampuan APBN untuk bermanuver, khususnya ketika terjadi krisis, memicu ketergantungan, dan membebani generasi yang akan datang.
Bukan itu saja, tingkat bunga (yield) utang relative mahal, karena diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.
Saat ini, tingkat yield SBN tenor 10 tahun di level 6,9%. Tertinggi dibandingkan dengan Malaysia (3,96%), Filipina (5,1%), Thailand (2,46%), Vietnam (5,47%), Singapura (2,1%), Korea Selatan (2,24%), China (3,55%), India (6,5%).
Yield yang tinggi inilah yang membuat pemodal asing terus memburu SBN. Hingga Juni 2017, total outstanding pemodal asing di SBN mencapai Rp 770,55 triliun atau sekitar 39% dari total SBN yang beredar di pasar.
Alhasil, ketika pemerintah membayar bunga SBN, maka pemodal asing inilah yang paling menikmatinya. Tahun ini, alokasi dana untuk membayar bunga utang mencapai Rp 221,2 triliun (16,8% dari total belanja pemerintah pusat).
Ironisnya, pemodal asing ini sewaktu-waktu bisa membawa keluar (capital outflow) keutungan investasi dari SBN itu, ketika terjadi perubahan sentimen. Dalam situasi inilah, rupiah akan cenderung tertekan dan menggerus cadangan devisa.
Selain itu, kubu yang kontra juga berpendapat bahwa rasio utang terhadap PDB tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk mengukur utang masih aman.
Sebab, jika diukur berdasarkan rasio penerimaan ekspor terhadap PDB (debt to service ratio/DSR) dan keseimbangan defisit primer, maka posisi utang pemerinta saat ini harus jadi perhatian serius.
Sampai kuartal I-2017, posisi DSR di level 52%. Artinya, setengah dari hasil ekspor digunakan untuk membayar utang. DSR ini naik tajam dibandingkan tahun 2012 yang di level 35%.
Sedangkan, defisit keseimbangan primer tahun 2016 telah menembus Rp 125,8 triliun. Naik tajam dari tahun 2102 sebesar Rp 52,8 triliun.
Per definisi, defisit keseimbangan primer merupakan hasil dari pengurangan penerimaan dengan belanja di luar pembayaran pokok dan bunga utang.
Makin melebarnya defisit keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan untuk membayar utang jatuh tempo berasal dari utang baru yang diterbitkan alias gali lubang tutup lubang.
Keniscayaan
Meskipun pemerintahan Jokowi-Kalla menyedot utang dalam jumlah besar dalam 2,5 tahun terakhir, tetapi tetapi ada beberapa kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan rezim sebelumnya.
Pertama, utang tidak lagi dipakai untuk membiayai subsidi yang tidak produktif, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik. Dalam tiga tahun terakhir, subsidi BBM dan Listrik mengalami pemangkasan yang siginifikan dari Rp 341,8 triliun (2014) menjadi Rp 77,3 triliun (2017). Sementara, belanja infrastruktur naik tajam dari Rp 264 triliun (2014) menjadi Rp 387,3 triliun (2017).
Ke depan, pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN untuk membangun infrastruktur dengan menggali potensi sumber-sumber pembiayaan non APBN (PINA), baik melalui pasar modal, sekuritisasi aset, BUMN, dan kerja sama sektor swasta.
Kedua mendorong efisiensi belanja dengan memangkas belanja yang tidak memberi efek pengganda pada perekonomian, seperti belanja barang. Tahun ini nilainya sebesar Rp 16 triliun.
Ketiga mendorong kualitas budgeting yang diharapkan dapat memperbaiki penyerapan belanja. Ini merupakan kelemahan terbesar yang sampai saat ini belum bisa hilang dari tubuh birokrasi. Buruknya kualitas penyerapan belanja inilah yang membuat tambahan utang menjadi mubazir.
Keempat mendorong dan memaksimalkan penerimaan, khususnya perpajakan. Harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak selama ini masih jauh dari potensinya.
Hal ini dapat tecermin dari kecilnya rasio wajib pajak terhadap jumlah penduduk dan rendahnya kepatuhan membayar pajak.
Kondisi inilah yang membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB dalam lima tahun terakhir mandek di level 10%-11%. Tertinggal jauh dari Malaysia (14%), Thailand (16%), Filipina (13%), Singapura (13%).
Untuk itulah, pemerintah telah menempuh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan menerbitkan Perpu nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan agar potensi pajak yang sangat besar itu dapat digali.
Pendek kata, jika tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan, khususnya pajak dan tidak ada perbaikan yang mendasar terhadap kualitas penganggaran belanja dan penyerapannya, maka penambahan utang merupakan sebuah keniscayaan.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya