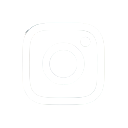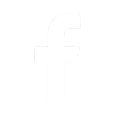Mengantisipasi Risiko Eksternal

Dalam satu bulan ke depan, kita akan meninggalkan tahun 2018. Harus diakui bahwa tantangan di tahun anjing tanah ini tidak lah mudah, khususnya di sektor ekonomi. Risiko global makin kerap bermunculan yang membuat proses pemulihan dan akselerasi ekonomi global menjadi tersendat.
Setidaknya, ada tiga risiko yang menjadi sorotan sepanjang tahun ini. Pertama, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu ke mana arah dan sebesar apa dampak dari perang dagang ini. Namun, menurut perhitungan Dana Moneter International (IMF), jika perang dagang terus berkecamuk, maka akan berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1 persen pada tahun 2019. Tahun 2019, PDB ekonomi global diperkirakan mencapai USD 92,7 trilun.
Itu juga sebabnya, IMF pada awal Oktober lalu telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi 3,7 persen (yoy) dari sebelumnya di April 2018 masing-masing sebesar 3,9 persen (yoy). Perang dagang ini juga berpotensi menciutkan pertumbuhan volume perdagangan global tahun 2018 dan 2019 menjadi 4,2 persen dan 4,0 persen dari tahun 2017 sebesar 5,2 persen. Menciutnya pertumbuhan volume perdagangan ini akan memukul kinerja harga komoditas global dan itu sekaligus menjadi berita buruk bagi negara-negara eksportir komoditas, seperti Indonesia.
Kedua risiko dari pasar finansial. Kebijakan moneter The Fed yang akan cenderung lebih hawkish dengan menaikkan suku bunga kebijakannya (fed funds rate/FFR). Kebijakan ini diperkirakan berlangsung sampai tahun 2020 untuk merespons akselerasi perekonomian AS. Dampaknya, membuat risiko di pasar finansial global, khususnya pasar keuangan bertumbuh (emerging market) meningkat.
Kebijakan The Fed ini mendorong investor global melakukan rebalancing portofolionya. Menarik keluar investasinya dari emerging market dan mengalirkannya masuk ke pasar keuangan AS. Imbasnya, pasar keuangan AS cenderung bullish. Sebaliknya, pasar keuangan di kawasan emerging cenderung bergejolak yang juga diikuti dengan pelemahan nilai tukar.
Argentina dan Turki menjadi dua negara di kawasan emerging yang perekonomiannya terkapar imbas dari pelemahan nilai tukar ini. Bahkan, Argetina harus meminta dana talangan (bailout) dari IMF sebesar USD 57,1 miliar untuk menghindarkan perekonomianya masuk ke jurang resesi.
Untuk merespons pelemahan nilai tukar dan gejolak pasar finansial ini, sejumlah negara di emerging pun harus menjalankan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga kebijakannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling agresif menaikkan suku bunga kebijakannya. Sepanjang Mei-November 2018, Bank Indonesia (BI) telah mengerek naik suku bunga kebijakan (BI-7DRR) sebesar 175bps menjadi 6 persen. Tren kenaikan BI-7DRR diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2019. Imbasnya, akan mendorong naik suku bunga pinjaman dan memperlambat mesin pertumbuhan.
Harga Minyak Dunia
Ketiga risiko kenaikan harga minyak dunia. Ketidakpastian pasokan di tengah permintaan yang cenderung stabil telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sepanjang Januari-Oktober 2018, harga rata-rata harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent telah naik masing-masing sebesar 34 persen dan 38 persen dari periode yang sama tahun lalu ke level USD 67 per berel dan USD 73 per barel.
Meski begitu, memasuki bulan November 2018, tren harga minyak dunia cenderung turun. Hal ini tidak terlepas dari melimpahnya pasokan. Meski begitu, ke depan, tren kenaikan harga minyak ini diperkirakan masih bisa berlanjut. Bahkan, Bank of America (BOA) memproyeksikan harga minyak dunia pada tahun 2019 bisa menembus level USD 100 per barel (Kontan.co.id, 11/5/2018).
Bagi Indonesia yang telah menjadi net importir minyak, lonjakan harga minyak ini akan memberikan konsekuensi bagi perekonomian, seperti mendorong inflasi naik dan memperburuk Defisit Transaksi Berjalan (DTB). Lonjakan harga minyak ini membuat pemerintah dalam posisi dilema. Jika, pemerintah menaikkan harga minyak, maka akan mendongkrak inflasi. Padahal, tahun politik sudah mendekat. Dan berdasarkan, teori siklus bisnis politik, kenaikan inflasi di tahun politik akan menurunkan popularitas petahana yang dapat mengancam keterpilahannya.
Itulah sebabnya, batalnya kenaikan harga premium beberapa waktu yang lalu cukup dapat dipahami. Ini sebagai upaya dari petahana untuk menjaga tingkat keterpilihannya. Namun, konsekuensi dari pilihan politik ini akan membuat meningkatnya beban subsidi. Sepanjang Januari-September 2018, realisasi subsidi BBM dan LPG telah mencapai Rp 54,3 triliun atau sebesar 115,9% dari pagu APBN 2018 sebesar Rp 46,9 triliun. Bahkan, dalam RAPBN 2019, subsidi BBM dan LPG pun dinaikkan sebesar Rp 3,1 triliun menjadi Rp 103,8 triliun.
Koordinasi Kebijakan
Mengingat risiko-risiko eksternal ini akan memberikan bertransmisi pada perekonomian domestik pada tahun 2019, maka pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat menjaga koordinasi dan solidalitas kebijakakan, sehingga dapat tetap menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memimalkan dampak dari risiko-risiko eksternal ini.
Mengingat Bank Indonesia (BI) masih akan melanjutkan stance kebijakan moneter yang tetap ketat (hawkish) pada tahun 2019 sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka pemerintah diharapkan dapat lebih memainkan peran lebih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah melalui APBN diharapkan dapat terus mendorong daya beli. Apalagi, tahun depan, faktor eksternal tidak bersahabat. Sehingga, konsumsi harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya, pemerintah harus memaksimalkan berbagai belanja sosial, khususnya dana desa, sehingga dapat mendorong daya beli kelompok bawah. Inflasi juga harus tetap dijaga di level rendah dan stabil.
Selanjutnya, pemerintah juga harus dapat memacu iklim investasi dan memberi insentif untuk menarik masuk investasi, khususnya investasi ke sektor padat karya. Harus diakui dalam tiga tahun terakhir, investasi memang tumbuh. Sayangnya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja justru melambat. Hal ini menunjukkan bahwa aliran investasi yang masuk masih didominasi oleh sektor padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat memberikan dukungan dengan mempermudah regulasi untuk mengakses pendanaan khususnya dari pasar modal bagi korporasi. Harus diakui bahwa sumber pendanaan dari sektor perbankan tahun depan akan makin ketat, seiring tren kenaikan suku bunga.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya