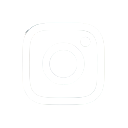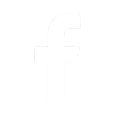Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Perekonomian dunia pasca pandemi sepertinya masih harus menapaki jalan terjal nan berbatu. Proyeksi dari berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter International (IMF), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sepakat memangkas pertumbuhan ekonomi global tahun 2023. Bahkan, dalam jangka menengah, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih tetap terbuka.
Sejumlah faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, seperti inflasi inti yang masih relatif tinggi, suku bunga yang tinggi, beban utang yang tinggi, perdagangan dan investasi global yang melambat imbas fragmentasi geopolitik yang meningkat, dan populasi yang cenderung menua.
Kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung melambat, bahkan terkontraksi akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang masih mendera. Daya beli dan investasi cenderung terpangkas. Sektor keuangan masih diliputi oleh ketidakpastian dan kerapuhan. Kebijakan fiskal ekspansif sulit diimplementasikan untuk menjadi bantalan (buffer) untuk menyerap shock, akibat defisit anggaran dan utang yang sudah terlanjur tinggi.
Di saat yang sama, China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang juga kerap jadi penyelamat, di kala perekonomian global mengalami kelesuan, ternyata juga mengidap perlambatan. Tingkat konsumsi dan investasi tetap lemah meski aktivitas ekonomi sudah direlaksasi pasca penguncian wilayah (lockdown) pada tahun 2022 lalu.
Menurut Michael Pettis, Guru Besar ilmu Keuangan dari Sekolah Managemen Guanghua, Universitas Peking, jika tidak ada terobosan kebijakan Pemerintah China untuk menyeimbangkan lagi kinerja konsumsi dan investasi, maka pertumbuhan ekonomi China di masa mendatang berpotensi turun ke di level sekitar 2-3% per tahun dari saat ini di level 4-5%.
Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara perekonomian besar dan diikuti dengan melambatnya harga komoditas global memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan.
Sepanjang Januari-Mei 2023, nilai akumulasi surplus neraca perdagangan turun sebesar 15.9% (yoy) dari periode yang sama tahun 2022 menjadi $ 16.6 miliar. Dampaknya, beberapa sektor berorientasi ekspor, seperti tekstil harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat lesunya pendapatan di tengah biaya yang meningkat.
Bukan itu saja, penurunan kinerja perdagangan ini juga memberikan dampak pada penerimaan pajak yang menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepanjang Januari-Mei 2023, penerimaan pajak tumbuh sebesar 17.7% (yoy) menjadi Rp 830.29 triliun. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dari periode yang sama tahun 2022 yang tumbuh sebesar 53.5% (yoy).
Menstimulasi Daya Beli
Di tengah kinerja pertumbuhan ekonomi global yang melambat itu, maka tumpuan pertumbuhanan pada konsumsi Rumah Tangga (RT). Sejauh ini, kinerja konsumsi masih relatif kuat. Hal ini tecermin dari sejumlah indikator, seperti Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) di atas 100 (optimis) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang tumbuh positif.
Untuk itulah, daya beli masyarakat harus terus distimulasi agar kinerja konsumsi sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi bisa lebih maksimal dan tidak merosot. Harapannya, momentum pemulihan ekonomi yang sudah terlihat sejak tahun 2022 berlanjut.
Stimulasi daya beli ini bisa dilakukan melalui kebijakan relaksasi moneter. Meski begitu, mengingat masih tingginya inflasi di negara-negara maju, membuat bank sentral, khususnya The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga, setidaknya dua kali lagi hingga akhir tahun ini.
Situasi ini, membuat Bank Indonesia (BI) akan memilih mempertahankan suku bunga kebijakan (BI-7DRR) di level 5.75% dan tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Kebijakan untuk mempertahankan suku bunga sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menjangkar inflasi agar berada dalam lintasan yang diharapkan.
Oleh sebab itu, kebijakan fiskal lebih efektif dalam menstimulasi daya beli. Apalagi, sampai dengan Mei 2023, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 204.3 triliun atau 0.97% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ekspansi fiskal masih terbuka lebar untuk dilakukan, tanpa mengabaikan konsolidasi fiskal, yaitu mengembalikan defisit APBN maksimal 3% dari PDB sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 2 tahun 2020.
Belanja fiskal bisa diarahkan dan diperbesar untuk menstimulasi sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja besar, seperti infrastrutkur dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, alokasi perlindungan sosial diperbesar dan distribusinya dipercepat agar bisa menyanggah daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Tentu saja, kebijakan pengendalian inflasi harus terus diperkuat. Meski dalam lima bulan terakhir, tren inflasi terus menurun imbas penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter ketat dari Bank Indonesia, tetapi harga sejumlah komoditas bahan pangan, seperti beras, daging ayam, telur, dan gula masih cenderung naik. Harga bahan pangan harus terus didorong turun dan distabilkan.
Bagaimana pun, sebagian besar pendapatan masyarakat dialokasikan untuk pengeluaran makanan dan transportasi. Sehingga, jika harga bahan pangan cenderung naik, maka akan mengurangi alokasi pengeluaran untuk non makanan, seperti belanja durables goods dan aktivitas leisure lainnya.
Berdasarkan, laporan “Pengeluran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2022” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (23/6) menyebutkan bahwa ketika pengeluaran per kapita per bulan masyarakat pada September 2022 sebesar Rp 1.39 juta atau naik 8.7% dari periode yang sama sebesar Rp 1.28 juta. Kenaikan pengeluaran ini terjadi akibat terjadinya lonjakan harga bahan pangan dan non pangan.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya