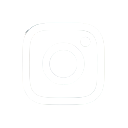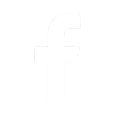Mengorbankan Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal II-2018 mencapai 5,27% (yoy). Hasil ini lebih baik dari periode yang sama tahun 2017 di level 5,06% (yoy) dan sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi kuartalan tertinggi sejak tahun 2013. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara sekawasan, capaian pertumbuhan ekonomi ini sangat baik. Pertumbuhan ekonomi China, Vietnam, India, dan Kamboja justru mengalami penurunan di kuartal II-2018.
Meski pertumbuhan ekonomi ini cukup menjanjikan, tetapi sejumlah risiko telah menghadang di depan, baik dari sisi eksternal dan internal. Sehingga, jika risiko ini tidak diantisipasi secara cermat dengan ramuan kebijakan yang tepat, terukur, dan kredibel, maka bisa memberikan dampak yang tidak positif pada perekonomian secara luas.
Sejumlah risiko eksternal yang saat ini patut diwaspadai, yaitu Pertama kenaikan suku bunga di negara-negara maju, khususnya dari Amerika Serikat (AS) akan memicu terjadinya aliran dana keluar (capital outflow) dari pasar keuangan di kawasan emerging market. Indonesia telah mengalaminya sejak awal tahun ini, khususnya dari pasar portofolio.
Aliran dana keluar (capital outflow) ini turut berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah. Dan, sampai saat ini, tren pelemahan rupiah ini masih terus berlanjut. Tekanan pada rupiah ini pun masih berpeluang berlanjut, seiring dengan pecahnya krisis nilai tukar di Turki dan Argentina. Krisis ini bisa memicu turunnya kepercayaan investor global pada perekonomian di kawasan emerging, yang bisa memperburuk aliran dana keluar.
Kedua perang dagang yang dilakukan oleh AS dengan sejumlah negara, khususnya China. Meski ekonomi Indonesia tidak terdampak signifikan terhadap perang dagang ini, seiring dengan kecilnya nilai transaksi perdagangan barang dan keuangan. Namun, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, maka jika ekonomi China tertekan oleh perang dagang ini, maka Indonesia akan turut merasakan dampaknya.
Ketiga kenaikan harga minyak dunia. Geliat pertumbuhan ekonomi dunia dan ketidakpastian produksi minyak global telah membuat tren kenaikan harga minyak dunia berlanjut. Harga minyak dunia ini pun telah jauh di atas asumsi harga minyak (ICP) di APBN 2018 sebesar $ 48 per barrel.
Di satu sisi, kenaikan harga minyak ini memberi keutungan bagi perekonomian Indonesia, khususnya terhadap penerimaan negara di APBN. Sampai dengan Mei 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 145 triliun. Hasil ini tumbuh sebesar 18,7% dari periode yang sama tahun 2017. Bahkan, target PNBP di APBN 2018 sebesar Rp 275 triliun bisa terlampaui.
Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak ini juga menggerus devisa mengingat posisi Indonesia sebagai net importir minyak. Bukan itu saja, beban subsidi yang juga meningkat, seiring dengan kebijakan pemerintah yang tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai tahun 2019.
Tingginya impor minyak inilah yang turut memberi kontribusi pada pemburukan Defisit Transaksi Berjalan (DTB). Pada kuartal II-2018, DTB mengalami pelebaran menjadi 3,04% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari kuartal I-2018 sebesar 2,21% dari PDB.
Mengorbankan Pertumbuhan
Kombinasi dari berbagai risiko tersebut telah berimbas pada kejatuhan nilai tukar rupiah. Sampai dengan (20/8/2018), nilai tukar rupiah telah melemah (depresiasi) sebesar 7,39% ke level Rp 14.569 per dollar AS dari awal tahun 2018.
Harus diakui bahwa pelemahan rupiah ini juga dialami oleh nilai tukar lainnya, termasuk nilai tukar di negara-negara maju, seperti Euro (Eropa), Yen (Jepang), dan Dollar (Kanada).Bahkan, pelemahan rupiah ini masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan nilai tukar negara lainnya, seperti India, Rusia, dan Afrika Selatan.
Meski begitu, pelemahan rupiah ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Apalagi, perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap kandungan impor. Sehingga, dengan melemahnya nilai tukar akan membuat harga produk impor meningkat yang pada akhirnya bisa mendorong inflasi (imported inflation).
Selain itu, pelemahan nilai tukar yang terus berlanjut bisa menambah beban pembayaran bunga Utang Luar Negeri (ULN) dan menurunkan kepercayaan investor asing, sehingga akan mendorong mereka menarik keluar investasinya.
Padahal, investasi asing ini masih dibutuhkan di tengah realitas masih terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah dan kapasitas pendanaan dari sektor keuangan domestik untuk membiayai pembangunan ekonomi. Di tengah situasi yang seperti ini, pilihan sulit harus diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Apakah membiarkan rupiah terus melemah atau mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Dan sepertinya Bank Indonesia dan pemerintah lebih memilih untuk mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, sejak Mei-Agustus 2018, Bank Indonesia mengerek naik suku bunga kebijakan (BI-7 days reverse repo rate/BI-7DRR) sebesar 125bps menjadi 5,5%. Hal ini dilakukan untuk menarik minat asing untuk kembali masuk dan memperkuat rupiah. Namun, kenaikan bunga ini akan mendorong kenaikan suku bunga kredit dan akan menekan kinerja pertumbuhan.
Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kebijakan BI ini. Sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi tekanan pada rupiah, seperti melakukan pembatasan terhadap 500 item barang-barang impor, mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, dan mempercepat implementasi mandatori B-20.
Bagi pemerintah ini bukan kebijakan yang mudah. Dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, maka akan dapat berimbas pada penciptaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itulah, tekanan nilai tukar rupiah ini harus jadi momentum bagi pemerintah untuk makin bekerja keras dalam memperbaiki struktur perekonomian, khususnya dalam menyehatkan Defisit Transaksi Berjalan (DTB). Bagaimana pun, jika struktur ekonomi Indonesia kokoh, meskipun gejolak eksternal menghadang, maka nilai tukar rupiah tidak akan dengan mudah bergoyang, seperti yang terjadi saat ini.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya