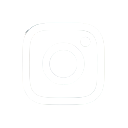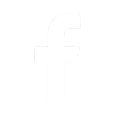Perekonomian di Tengah Bayang-bayang Resesi

Presiden Joko Widodo telah membacakan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) 2020 beserta nota keuangannya pada 16 Agustus 2019 lalu. Asumsi indikator makroekonomi yang ditetapkan, yaitu (i) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (yoy); (ii) tingkat inflasi sebesar 3,1% (yoy); (iii) SPN 3 bulan sebesar 5,4%; (iv) nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.400 per dollar AS; (v) harga minyak (ICP) sebesar USD 65 per barel; (vi) lifting minyak dan gas masing-masing sebesar 734 ribu barel per hari (rbph) dan 1.191 ribu barel per hari setara minyak (rbphsm).
Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 2.221,5 triliun, di mana sekitar 84% akan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.861,8 triliun. Belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.528,8 triliun, di mana belanja ini akan difokuskan untuk mendorong daya beli dan menstimulasi mesin investasi. Alhasil, defisit diperkirakan sebesar Rp 307,22 triliun (1,76% dari PDB). Untuk membiayai defisit ini, pemerintah akan menarik utang baru sebesar Rp 351 triliun tahun 2020.
Di samping itu, Jokowi juga memaparkan sejumlah capaian pengelolaan ekonomi dalam empat tahun terakhir, seperti (i) pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03% per tahun sepanjang 2015-2018; (ii) rata-rata inflasi sebesar 3,5% per tahun sepanjang 2016-2018; (iii) tingkat kemiskinan yang turun dari 5,81% (2015) menjadi 5,01% (2019); (iv) Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio gini yang juga turun dari 0,41 (2014) menjadi 0,382 (2019).
Meski pengelolaan ekonomi domestik relatif cukup baik, tetapi tantangan yang dihadapi cukup berat. Dari sisi eksternal, kinerja pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat (menuju resesi). Tingkat inflasi dan produktivitas global yang cenderung turun. Tingkat utang korporasi global cenderung naik. Dan, pasar finansial global makin kerap bergejolak.
Tantangan perekonomian global ini makin bertambah berat, karena Amerika Serikat (AS) dan China yang merupakan dua raksasa ekonomi global terlibat perang dagang. Aksi balas (retaliation) terus berlanjut melalui penaikan tarif perdagangan. Meski telah dilakukan dua kali perundingan, tetapi selalu menemui jalan buntu.
Perang dagang membuat aktivitas perdagangan global dan harga komoditas global makin meredup. Sepanjang kuartal I-2019, perdagangan global hanya tumbuh sebesar 0,5% (yoy). Hasil ini merupakan kinerja terendah sejak tahun 2012. Lesunya kinerja perdagangan global ini membuat aktivitas manufaktur global merosot dan akan memukul kinerja daya beli. Pendek kata, efek perang dagang ini akan membuat pertumbuhan ekonomi global makin suram.
Suramnya kinerja pertumbuhan ekonomi global ini tecermin dari proyeksi Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia yang pada Juli 2019 lalu kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 masing-masing menjadi 3,2% (yoy) dan 2,6% (yoy) dari sebelumnya 3,3% (yoy) dan 2,9% (yoy).
Jalur Transmisi
Efek perang dagang ini akan mengenai perekonomian Indonesia melalui dua jalur transmisi. Pertama melalui jalur perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia sepanjang tahun ini melambat. Sepanjang Januari-Juli 2019, realisasi ekspor mencapai USD 95,5 miliar atau turun 8,1% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu.
Merosotnya kinerja ekspor ini akibat lesunya harga komoditas (CPO dan Batubaru) dan lesunya perekonomian mitra-mitra dagang, khususnya China. Menurut Bank Dunia, penurunan pertumbuhan ekonomi China sebesar 1 poin persen menurunkan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 0,3 poin persen.
Lesunya kinerja perdagangan ini membuat defisit neraca berjalan (CAD) berimbas pada kinerja neraca berjalan (CAD). Sepanjang kuartal II-2019, CAD mencapai USD 8,4 miliar (3% dari PDB) atau melebar dari kuartal I-2019 sebesar USD 6,2 miliar (2,6% dari PDB). Melebarnya CAD ini akan membuat tekanan terhadap rupiah tidak terhindarkan. Untuk mengobati pemburukan CAD ini, maka pemerintah melambatkan laju pertumbuhan impor yang implikasinya akan mendorong pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Kedua melalui jalur keuangan. Indonesia merupakan negara yang memiliki ketimpangan pembiayaan yang cukup besar. Tabungan domestik tidak mencukupi untuk membiayai investasi domestik. Alhasil, aliran modal eksternal dibutuhkan, baik melalui investasi langsung (FDI) yang berjangka panjang dan berkelanjutan maupun investasi portofolio yang bersifat jangka pendek dan tidak stabil.
Masalahnya, aliran modal eksterna lebih didominasi oleh investasi portofolio. Lihat saja, tren kenaikan kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) terus terjadi. Padahal, aliran modal portofolio ini sangat rentan dengan perubahan sentimen yang dapat memicu pembalikan arus modal (capital outlflow) yang implikasinya dapat mendistorsi stabilitas makroekoomi, khususnya nilai tukar.
Hal ini yang kembali diingatkan oleh Bank Dunia baru-baru ini, di mana pasar keuangan Indonesia sangat rentan mengalami pembalikan arus modal (capital outflow). Berdasarkan pengalaman, pembalikan arus modal ini bersifat destruktif dan menghasilkan ongkos yang besar, seperti yang terjadi pada tahun 2013 (tapering off dari The Fed) dan tahun 2018 (efek perang dagang dan kebijakan pengetatan moneter dari The Fed.
Meski begitu, melihat gelagat dari otoritas moneter di negara-negara maju yang akan cenderung untuk menempuh stance kebijakan moneter longgar dan Quantitave Easing (QE) untuk melawan resesi ekonomi global, maka efek dari perang dagang ini terhadap perubahan arus modal global tidak akan menimbulkan efek kejutan dan kerusakan sehebat yang terjadi pada tahun 2013 dan 2018. Itulah sebabnya, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjaga koordinasi dan komunikasi agar dapat melewati tekanan di pasar keuangan ini dengan baik.
Terobosan kebijakan
Di tengah atmosfir perekonomian global yang cenderung melambat dan berbungkus ketidakpastian, maka pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola perekonomian. Perekonomian tidak bisa lagi dikelola secara business usual. Apalagi, kinerja pertumbuhan ekonomi domestik cenderung stagnan di level 5%.
Jika pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa diungkit lebih tinggi, maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hasilnya, dividen demografi yang sedang terjadi saat ini tidak akan memberikan dorongan besar. Indonesia pun terlanjut menua sebelum kaya.
Untuk mencegah hal ini, maka pemerintah sebagai pemegang mandat dalam menentukan aturan main dituntut untuk dapat melahirkan terobosan-terobosan kebijakan, khususnya dalam menarik aliran investasi langsung (FDI) untuk mendorong dan memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi. Investasi langsung ini dibutuhkan untuk mengimbagi investasi jangka pendek di portofolio, sehingga ketika ketidakpastian di pasar keuangan meningkat tidak membuat ganguan stabilitas makroekonomi menghebat.
Sebenarnya, Indonesia menjadi salah satu ‘darling’ bagi investor global, setelah China dan India. Hal ini tidak terlepas dari populasi yang besar dengan kelas menengah yang terus membesar dengan cakupan pasar yang sangat luas. Tidak banyak negara, seperti Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki sektor-sektor unggulan yang sangat prospektif, seperti pariwisata, manufaktur, petrokimia dan tekstil, elektronik, energi, kelautan, dan industri kreatif.
Dengan potensi yang begitu besar itu, investor global harusnya berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Namun, faktanya itu tidak terjadi. Salah satu contohnya, dari 33 perusahaan yang melakukan relokasi dari China akibat dampak perang dagang, sekitar 23 memilih berinvestasi ke Vietnam dan 10 perusahaan lain memilih Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Indonesia pun tidak dilirik sama sekali.
Menurut Bank Dunia, dalam lima tahun terakhir, rata-rata investasi langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia hanya 1,9% terhadap PDB. Hasil ini lebih rendah dari Kamboja sebesar 11,8% dari PDB, Vietnam sebesar 5,9% dari PDB, Malaysia sebesar 3,5% dari PDB, dan Thailand sebesar 2,6% terhadap PDB.
Apa yang membuat investor global enggan melirik Indonesia? Tentu, akibat kombinasi dari kakunya regulasi dan kelembagaan, terbatasnya kemampuan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), dan mahalnya biaya logistik. Dalam Ease of Doing Business (EODB) tahun 2019 dari Bank Dunia, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 73. Jauh di bawah Vietnam di level 69.
Indonesia juga dikenal dengan ekonomi biaya tinggi yang tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang saat ini di level 6,3%. Lebih tinggi dari Malaysia (4,6), Filipina (3,7%), Thailand (4,5%), dan Vietnam (5,2%). Inilah pekerjaan besar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam lima tahun ke depan untuk melahirkan terobosan-terobosan kebijakan yang inovatif agar investasi langsung masuk (FDI).
Jika hal itu tidak dilakukan dengan cepat, maka Indonesia hanya akan menjadi raksasa ekonomi yang terus tertidur. Enggan menunjukkan kekuatan besarnya. Ramalan dari Standard Charted, Plc yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan menjadi kekuatan keempat terbesar di dunia pada tahun 2030 hanya akan menjadi ramalan saja. Namun, ketika semua berharap, ramalan ini bisa menjadi kenyataan. Semoga.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya