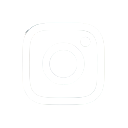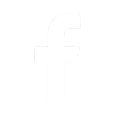Rupiah dan Devisa Berkelanjutan

Sejak awal bulan Februari 2018, tren pelemahan nilai tukar rupiah terus terjadi. Bahkan saat ini, rupiah masih cerderung bergerak di level Rp 13.800-Rp 14.000 per dollar AS. Level rupiah ini jauh di atas asumsi APBN 2018 di level Rp 13.400 per dollar AS.
Dinamika ekonomi global, khususnya dari Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi gejolak nilai tukar rupiah ini. Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun terakhir, perekonomian AS terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tecermin dari inflasi yang cenderung naik dan saat ini level 2,9% (yoy) dan tingkat pengangguran yang turun ke level 4%.
Perbaikan ekonomi ini membuat bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) harus menempuh kebijakan moneter ketat melalui kenaikan suku bunga kebijakan (federal funds rates/FFR) untuk mengantisipasi terjadinya pemanasan (overheating) terhadap perekonomian.
Sejak tahun 2015, FFR ini telah disesuaikan secara bertahap. Sampai akhir tahun 2018, FFR diperkirakan akan bertengger level 2%-2,25%. Di tahun 2019 diperkirakan akan berlanjut naik hingga ke level 2,75%-3%.
Kenaikan FFR ini juga diikuti dengan kebijakan Quantitative Tightening (QT) yang akan berimplikasi pada tersedotnya likuiditas global. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun 2009-2013, The Fed menjalankan kebijakan Quantitative Easing (QE) dengan total $ 4,2 triliun untuk menjaga pemburukan ekonomi, seperti yang terjadi pada krisis besar tahun 1930.
Implikasi dari kebijakan QE ini membuat harga aset, khususnya di sektor keuangan (saham dan obligasi) dan nilai tukar di kawasan emerging mengalami kenaikan yang luar biasa (boom). Kawasan emerging manjadi ‘sasaran’ dana dari QE ini, karena memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi.
Namun, ketika kebijakan QE mulai diketatkan pada tahun 2013, maka pembalikan dana, khususnya dari emerging market tidak dapat dihindarkan. Dan perlu dicatat bahwa dalam setiap siklus pembalikan, maka harga aset keuangan dan nilai tukar juga akan ikut tertekan dan bergejolak.
Jika dilihat sejak Januari-Juni2018, rupiah telah melemah sekitar 6%. Namun, pelemahan rupiah ini masih relatif baik dibandingkan dengan pelemahan nilai tukar sekawasan, seperti India, Filipina, Turki, Brazil, dan Argentina. Bahkan, pelemahan rupiah saat ini masih relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, ketika terjadi taper tantrum. Kala itu, rupiah melemah hampir 20%.
Imbas Pelemahan Rupiah
Meski begitu, pelemahan rupiah ini tidak bisa dibiarkan berkelanjutan, karena bisa memicu dampak yang tidak diharapkan terhadap perekonomian. Apalagi, sampai saat ini, perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor, khususnya bahan baku dan bahan penolong.
Pelemahan rupiah akan membuat harga komponen impor menjadi mahal. Kondisi ini akan menggerus margin keuntungan dunia usaha. Strategi dunia usaha (produsen) untuk mengatasinya ialah dengan menaikkan harga barang. Kondisi inilah yang bisa mendorong naiknya inflasi. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, tingkat inflasi cukup bisa dijaga di level yang rendah dan stabil.
Selain itu, pelemahan rupiah juga akan membuat beban pembayaran bunga dan pokok Utang Luar Negeri (ULN) meningkat, khususnya bagi korporasi/entitas yang tidak melakukan kebijakan lindung nilai (hedging).
Bukan itu saja, pelemahan nilai tukar rupiah yang terlalu lama juga mendorong menurunnya kepercayaan investor asing, khususnya di sektor portofolio. Mereka akan melakukan aksi jual untuk menghindari rugi kurs (forex loss) yang lebih besar. Situasi seperti inilah yang turut memperburuk kinerja rupiah.
Jika dilihat di pasar saham, sejak Januari-Juni 2018, investor asing telah melakukan aksi jual bersih (net sell) lebih dari Rp 50 triliun. Kondisi inilah yang membuat IHSG mengalami gejolak yang luar biasa. Jika pada (19/2/2018), IHSG sempat menyentuh level 6.689. Namun, pada (21/5/2018), IHSG meluncur ke level 5.733. Artinya, dalam tempo tiga bulan itu, IHSG telah terpangkas sebesar 14%.
Kondisi yang sama juga terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Investor asing cukup agresif melakukan aksi jual, khususnya di bulan April-Mei 2018. Dalam dua bulan itu, total dana asing yang keluar Rp 29 triliun. Kondisi ini membuat yield acuan 10 tahun melompat level 7,5% (23/5/2018). Padahal, pada (12/1/2018), yield acuan 10 tahun sempat menyentuh level 6,01%.
Melonjaknya yield ini berimplikasi pada mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam penerbitan SBN sebagai sumber utama pembiayaan defisit APBN.
Kebijakan Stabilisasi
Sejumlah langkah telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang diberi mandat untuk menjaga stabilisasi rupiah. BI cukup agresif melakukan intervensi, baik di pasar valas dan SBN alias intervensi kembar. Hasilnya, cadangan devisa telah tergerus hampir $ 9 miliar sejak Januari-Juni 2018. Masalahnya, intervensi ini belum banyak memberikan perbaikan pada rupiah. Sebaliknya, rupiah masih cenderung melemah dan bergejolak.
Sampai dengan Mei 2018, BI akhirnya menaikkan suku bunga kebijakannya (BI-7 Days Reverse Repo Rate/7-DRR) sebesar 50bps menjadi 4,75% dan kembali dinaikkan pada Juni 2018 sebesar 50bps. Sehingga, sepanjang Mei-Juni 2018, BI-7DRR telah naik 100bps menjadi 5,25%. Langkah BI ini disebut sebagai langkah pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve. BI telah memberi sinyal bahwa ruang penaikan BI-7DRR ke depannya masih bisa terjadi, sekiranya tekanan terhadap rupiah masih terus terjadi.
Perlu dicatat bahwa langkah untuk menaikkan suku bunga kebijakan ini juga telah dilakukan oleh sejumlah otoritas moneter di kawasan emerging sebelumnya,seperti Meksiko (25bps), China (5bps), Filipina (50bps), dan Malaysia (25bps).
Harus diakui dengan berakhirnya era suku bunga rendah di negara maju, khususnya AS, membuat spread suku bunga dengan emerging makin menipis. Sehingga, jika spread ini tidak disesuaikan, maka bisa memengaruhi daya tarik investor global untuk mengalirkan investasinya.
Padahal, investasi asing itu masih dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia di tengah kenyataan terbatasnya sumber pembiayaan dari pasar keuangan domestik. Namun, di sisi lain, kenaikan suku bunga juga akan memicu kenaikan suku bunga pinjaman yang pada akhirnya dapat mengganjal kinerja pertumbuhan ekonomi.
Devisa Berkelanjutan
Mengingat posisi rupiah cukup rentan, ketika dinamika perekonomian global terjadi, maka Indonesia harus berupaya untuk menarik devisa yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dan tidak lagi terlalu bergantung pada devisa yang bersifat jangka pendek (hot money).
Untuk merealisasikan ini, maka sejumlah kebijakan harus terus diarahkan pada tujuan tersebut. Pertama, mempercepat revitalisasi Industri manufaktur yang akan mendorong daya saing produk ekspor Indonesia. Indonesia harus secara bertahap mengurngi ketergantungan pada produk komoditas mentah (raw material).
Kebijakan ini juga harus diikuti secara pararel dengan pengembangan industri bahan baku dan bahan penolong.
Setiap tahunnya, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang sangat besar untuk mendatangkan bahan baku dan penolong. Apalagi, ketika pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat.
Dengan berkembangnya industri ini, maka selain dapat menghemat devisa, juga diharapkan dapat memperbaiki Defisit Transaksi Berjalan (DTB). Indonesia harus dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya. Tentu untuk dapat mendorong berkembangnya industri ini, maka dibutuhkan iklim investasi yang kondusif dan ramah. Ini pekerjaan rumah yang berat. Sering dibicarakan sekaligus dikeluhkan, tetapi sulit direalisasikan. Untuk itulah, pemerintah pusat dan daerah harus terus bahu-membahu untuk merealisasikannya.
Kedua mendorong diversifikasi energi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat kebutuhan sumber energi ikut meningkat. Masalahnya, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap energi fosil (BBM) yang saat ini produksinya jauh di bawah konsumsinya.
Sehingga untuk menutupi selisih (gap) ini, pemerintah harus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang tentunya menggerus devisa.
Padahal, Indonesia memiliki sumber energi baru dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Selain itu, jika energi baru dan terbarukan ini dapat diubah jadi produk, maka bisa dijual sebagai sumber devisa baru.
Kedua menggejot kemampuan sektor pariwisata. Indonesia memiliki pesona alam yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa dan juga pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kemampuan Indonesia untuk menyedot devisa dari sektor ini masih relatif tertinggal dari negara tetangga.
Sebagai contoh, devisa yang diperoleh Indonesia dari sektor pariwisata sepanjang tahun 2016 mencapai $ 11,3 miliar. Hasil ini masih jauh lebih rendah dari Thailand sebesar $ 49,9 miliar dan Malaysia sebesar $ 18,1 miliar. Dengan melihat data ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah di sektor pariwisata yang harus diperbaiki dan terus digenjot. Apalagi, pemerintah telah mencanangkan bahwa sektor pariwisata akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Keempat meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia. Remintasi yang dikirim oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi salah satu sumber devisa yang berkesinambungan. Data Bank Indoensia mencatatat bahwa sepanjang tahun 2017, nilainya remitansi mencapai Rp 108 triliun.
Tentu, nilai remitansi ini masih bisa lebih besar, jika makin banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki skill yang lebih baik, sehingga bisa masuk ke sektor-sektor yang dapat memberikan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Indonesia bisa meniru kebijakan Filipina yang sangat concern untuk memperlengkapi tenaga kerja mereka di luar negeri dengan skill yang mumpuni, khususnya dalam hal bahasa asing.
Kembali
Kembangkan Skala Finansial Anda
Investasi Sekarang
Jangan biarkan kesempatan berlalu, kami siap membantu anda meraih masa depan yang lebih baik.
Daftarkan diri anda melalui online form kami atau jika anda membutuhkan informasi lebih, biarkan petugas kami yang menghubungi anda.
Form Investasi Hubungi Saya